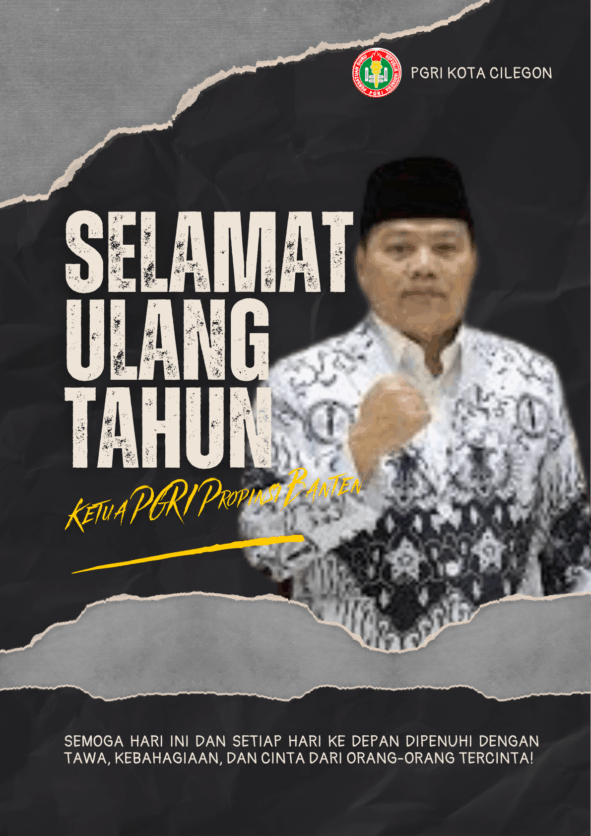Pendidikan di awal Indonesia merdeka menjadi aspek penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Perhatian pemerintah yang baru lahir dan para tokoh revolusioner menyadari bahwa pendidikan sangat penting untuk menanamkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka.
Proklamasi kemerdekaan menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan cita-cita nasionalisme yang selama ini menjadi alat pemersatu para pejuang. Semangat ini mendorong perjuangan guru-guru Indonesia untuk:
- Mempertahankan kemerdekaan dengan mendidik bangsanya agar menjadi manusia yang cerdas dan berpengetahuan.
- Memberikan kesadaran akan semangat perjuangan kepada anak didiknya, selain ikut membantu para tentara dan masyarakat dalam melawan Belanda.
Perubahan di bidang pendidikan yang terjadi pasca-proklamasi kemerdekaan bersifat mendasar, yaitu menyesuaikan dengan cita-cita bangsa dan negara yang baru merdeka.
Landasan Idiil dan Tujuan Pendidikan
Landasan Idiil: Dasar dan falsafah negara Indonesia adalah Pancasila, yang kemudian dijadikan landasan idiil pendidikan Indonesia.
Perumusan Landasan: Panitia Penyelidik Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara berhasil merumuskan landasan idiil Pancasila, tujuan pendidikan, sistem sekolah, serta kesempatan belajar bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
Tujuan Pendidikan: Pendidikan dirumuskan bertujuan mendidik warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Penekanan tujuan pendidikan pada masa ini adalah menanamkan semangat dan jiwa kepahlawanan (patriotisme).
Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran Baru
Pada tanggal 29 Desember 1945, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan agar pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru, yang meliputi:
- Mengganti paham perseorangan dengan paham kesusilaan dan peri kemanusiaan yang tinggi, serta membimbing murid menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
- Mengadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat demi memperkuat persatuan rakyat.
- Pendidikan dan pengajaran hendaklah berdasarkan sistem sekolah kerja agar aktivitas rakyat terhadap pekerjaan biasa berkembang seluas-luasnya.
- Pengajaran agama mendapat tempat yang teratur, dan Madrasah/Pesantren mendapat perhatian serta bantuan nyata dari pemerintah.
Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia adalah hasil dari perjuangan guru-guru Indonesia. Sejarah perjuangan guru telah dimulai sejak masa Hindia Belanda dengan Persatuan Guru Hindia Belanda (1912) dan kemudian Persatuan Guru Indonesia (1932).
Kongres Pertama Guru (24-25 November 1945)
Pelaksanaan: Kongres Guru dilaksanakan di Sekolah Guru Puteri (SGP) gedung Van De Vanter, Surakarta, Jawa Tengah.
Penggerak: Kongres digerakkan dan dipimpin oleh Amin Singgih dan Rh. Koesnan.
Kesepakatan: Guru-guru sepakat untuk membentuk organisasi yang bisa mewadahi aspirasi dan perjuangan guru untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Nama PGRI: Atas usulan dari Persatuan Guru Seluruh Priangan (PGSP) dari Jawa Barat, organisasi tersebut dinamakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Jati Diri: PGRI lahir sebagai manifestasi aspirasi kaum Guru Indonesia dalam mengambil bagian dan tanggung jawab sesuai dengan bidang profesinya sebagai pendidik untuk mengisi kemerdekaan. Organisasi ini dipandang sebagai pemersatu kaum guru yang bersifat: 1) unitaris, 2) independen, dan 3) non partai politik.
Tiga Tujuan Mulia PGRI
Kongres Pertama PGRI merumuskan tiga tujuan mulia, yang mencerminkan sifatnya sebagai organisasi pelopor dan pejuang:
- Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
- Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran dengan dasar kerakyatan.
- Membela hak dan nasib buruh umumnya, serta hak dan nasib guru khususnya.
PGRI menetapkan dirinya sebagai organisasi pejuang yang turut mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI.
Peran dalam Perjuangan Fisik dan Politik
Perjuangan Fisik: Saat revolusi bergelora, guru-guru ikut membantu tentara dan masyarakat melawan Belanda. Guru-guru rela meninggalkan tugasnya, bahkan tidak jarang menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan guru perempuan bertugas di dapur umum atau Palang Merah Indonesia (PMI). Tidak sedikit dari mereka yang gugur sebagai pahlawan.
Peran Politik: Dua orang wakil PGRI ditunjuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tokoh PGRI, Rh. Koesnan, diangkat menjadi anggota Panitia Gaji Pemerintah dan kemudian menjadi Menteri Perburuhan dan Sosial pada Kabinet Moh. Hatta.
Tuntutan dan Amanat Penting
- Kongres Kedua (21-23 November 1946): Kongres ini menghasilkan tiga tuntutan kepada pemerintah:
- Sistem pendidikan dilakukan atas dasar kepentingan nasional.
- Gaji guru supaya tidak dihentikan.
- Diadakannya Undang-undang Pokok Pendidikan dan Undang-undang Pokok Perburuhan.
- Amanat Presiden Soekarno: Presiden menegaskan bahwa guru adalah pembentuk manusia seutuhnya, pendidik rakyat ke arah kejayaan dan keagungan bangsa, dan harus menjadi pelopor dalam menghadapi perjuangan dan pembangunan negara.
Kongres Ketiga (27-29 Februari 1948): Kongres darurat ini menegaskan kembali haluan dan sifat perjuangan PGRI:
- Mempertahankan NKRI.
- Meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai falsafah Pancasila/UUD 1945.
- Tidak bergerak dalam lapangan politik (nonpartai politik).
- Menerbitkan majalah Guru Sasana (Suara Guru) sebagai sarana komunikasi.
Peran PGRI yang paling utama adalah mempelopori perubahan sistem pendidikan kolonial ke arah sistem pendidikan nasional. PGRI berjuang mengembangkan pendidikan Indonesia dengan bernafaskan peralihan dari pendidikan yang bersifat kolonial ke pendidikan Nasional.
Berikut adalah rujukan/sumber utama yang digunakan dalam penyusunan riwayat sejarah ini (Diambil dari Daftar Rujukan pada dokumen 916-2589-1-PB.pdf):
- Depdikbud.1979
- Kahin, George Mc. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono.. dkk. 1975. Sejarah Nasional Indonesia Jilid III.
- Ricklefs, M.C., 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008.
- PGRI., 2008. Buku Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI.
- Hadiatmadja, R.A. Soepardi., dkk., 2000. Pendidikan sejarah perjuangan PGRI (PSP-PGRI), Jilid II, III, IV, V.
- Yunus., 2003. PGRI dari masa ke masa.